SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

YOGYAKARTA, Indonesia – Sepanjang malam, pada 22 Oktober 1965, suasana begitu mencekam di Klaten. Bunyi kentongan tanda bahaya bertalu-talu, bersahutan, dan terdengar jelas oleh penduduk Manisrenggo, Prambanan, Depo, dan Jogonalan. Semua orang diliputi ketakutan dan kecemasan. Sesuatu yang misterius sedang terjadi dan akan mengubah hidup mereka.
Malam itu, kekerasan meletus di beberapa wilayah melibatkan pemuda rakyat, PKI, dan militer. Kejadian malam itu dikenal dengan peristiwa Kenthong Gropyok yang menjadi prolog pembantaian “kaum merah” di wilayah tersebut. Keesokan harinya, 23 Oktober 1965, anti-klimaks terjadi. Orang-orang komunis (dan yang dituduh komunis) diburu. Partai dan ormas mereka dihancurkan.
Peristiwa ini merupakan penggalan cerita dari buku Prahara di Garis Merah, yang bertutur tentang sejarah aksi kekerasan dan penghancuran Partai Komunis Indonesia (PKI) di Klaten dan Boyolali periode 1965-1979. Buku itu juga menceritakan sejumlah peristiwa yang mengobarkan permusuhan dan berakhir dengan pembantaian para pendukung komunis.
Karya Kuncoro Hadi dan kawan-kawan ini merupakan kajian sejarah lisan tentang detil konflik lokal pra dan pasca Oktober 1965 di dua kabupaten yang merupakan kantong pendukung partai palu arit di Jawa Tengah. Kuncoro mendasarkan penelitiannya pada sumber primer – para penyintas dan saksi peristiwa – serta dokumen seperti surat kabar pada zaman itu.
Selain judul itu, Kuncoro juga menulis Kronik 65 yang merupakan hasil penelitiannya tentang relasi antara PKI dan partai lain, pemerintahan Soekarno, dan militer, dari 1963 hingga 1971, serta rangkaian peristiwa demi peristiwa rinci yang terjadi sepanjang Oktober 1965.
Sayangnya, buku-buku langka ini tak akan segera bisa dinikmati para pembaca sejarah kiri Indonesia. Sejak isu sweeping buku kiri dan atribut palu-arit, Kuncoro dan kawan-kawan merasakan dampaknya secara langsung – buku-bukunya terancam pemberangusan.
“Kemarin pihak penerbit Narasi di Yogyakarta didatangi polisi dari Polresta dan Polda DIY. Akhirnya, penerbitan buku-buku saya terpaksa ditunda terus,” ujar Kuncoro saat berbincang dengan Rappler, Kamis, 19 Mei.
Polisi meminta dan menyita sampel buku-buku kiri dari penerbit. Beruntungnya, sampel buku karya Kronik 65 yang sudah masuk proses penyuntingan akhir itu tersembunyi dan lolos dari aparat.
Sebenarnya buku itu hanya menunggu kata pengantar dari Asvi Warman Adam, sejarawan senior dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Namun, saat bertemu Kuncoro, Asvi menyarankannya untuk sementara menunda penerbitan buku tersebut karena situasi yang tidak mendukung. Tetapi, Kuncoro menginginkan paling lambat Oktober tahun ini bukunya sudah bisa beredar.
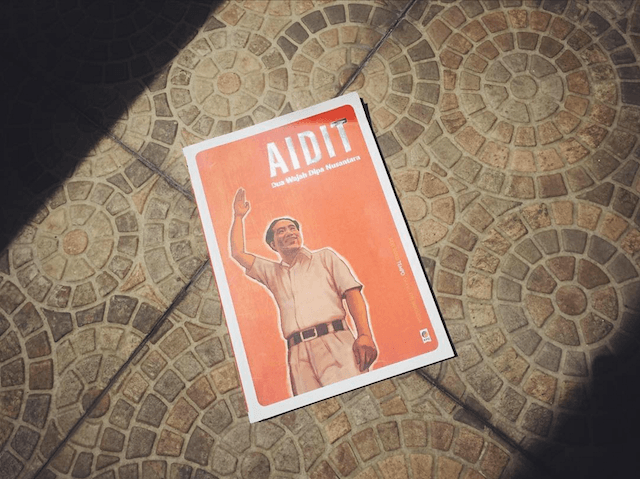
Sementara buku Prahara di Garis Merah juga tak bebas dari masalah. Sebenarnya, penerbit Narasi merencanakan cetak dan edar tahun kemarin, namun terpaksa batal karena penerbit tidak bisa menjual bukunya. Selama ini Narasi bermitra dengan Gramedia sebagai toko buku untuk memasarkan buku-bukunya, namun kali ini Gramedia menolak judul buku sejarah yang ditulis Kuncoro.
Bedah buku yang direncanakan digelar di Balai Soedjatmoko Bentara Budaya Solo ini juga batal. Selain faktor penolakan Gramedia, pihak penyelenggara diskusi juga mengaku sulit menggelar acara bedah buku semacam itu karena ada peringatan dari kepolisian.
“Acara semacam itu banyak tekanan dari aparat dan ormas. Kami sendiri sering ditelepon dari Polres dan dengan ancaman tidak mau tanggung jika ada terjadi apa-apa,” ujar pengelola acara Balai Soedjatmoko, Yunanto Sutyastomo.
Penerbit dan penulis akhirnya sepakat untuk mencetaknya dalam jumlah terbatas untuk dijual sendiri secara online dan diedarkan di luar Gramedia. Tetapi, merebaknya isu anti buku kiri membuat penerbit kembali mengurungkan niatnya.
Kuncoro sendiri mengecam pelarangan buku-buku pengetahuan dan sejarah gerakan kiri, terutama yang menyangkut peritiswa ’65, yang seharusnya bisa diakses oleh semua orang. Buku-buku sejarah, kata dia, seharusnya lebih banyak lagi diterbitkan agar diketahui publik, bukan malah dipersulit dan diberangus peredarannya.
“Peristiwa ’65 itu kan satu bagian dari sejarah Indonesia yang paling gelap pasca kemerdekaan, saya yakin banyak anak muda yang ingin tahu tentang periode ini berikut dampaknya,” kata Kuncoro yang juga mengaku anak mantan tahanan politik Orde Baru ini.
Generasi sekarang, kata Kuncoro, masih bagian dari generasi Orde Baru yang mewarisi wacana anti-komunisme yang sangat kuat sehingga masih alergi terhadap sesuatu yang berbau kiri. Propaganda terhadap PKI dan komunisme sudah mendarah daging, karenanya ia ragu bahwa pengungkapan kebenaran peristiwa ’65 akan terjadi dalam waktu dekat – dalam masa pemerintahan Joko Widodo.
“Beruntungnya, kini mulai bermunculan orang-orang kritis yang berani bertanya dan melihat kasus 65 dengan cara berbeda,” ujar Kuncoro.
Selain Narasi, polisi dan tentara pekan lalu juga mendatangi penerbit Resist Book yang dituding memproduksi buku-buku berbau komunis di Yogyakarta. Perwakilan Resist Book Indro Suprogo mengaku sangat terteror dengan kedatangan aparat ke penerbit. Meskipun tidak ada penyitaan, penerbit harus meladeni aparat untuk diskusi panjang tentang buku mereka.
Sementara, sweeping juga terjadi di toko-toko buku, salah satunya di Shopping Center. Petugas Kejaksaan Tinggi DIY menyita buku Sejarah Gerakan Kiri di Indonesia dari pedagang di pusat bursa buku terbesar di Yogyakarta itu. Penjual diberi peringatan untuk tidak lagi menjual buku yang dianggap kiri.

Razia buku di mendapat protes dari Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), yang menganggapnya sebagai tindakan aparat yang berlebihan. Ketua IKAPI Yogyakarta, Akhmad Fikri, menyebut bahwa komunisme sudah mati sejak Soviet bangkrut sehingga tidak perlu takut dengan ideologi kiri itu. Selain itu, kata dia, membaca buku kiri tak akan serta merta membuat orang menjadi komunis.
Soal gerakan anti-kiri sebenarnya sudah ada sebelum ramainya isu rekonsiliasi, simposium, dan kuburan massal korban ’65. Tetapi, ancaman terhadap buku kiri sudah ada sejak dekade pertama reformasi. Tumbangnya rezim militer Soeharto tidak serta merta mengubah cara pandang manusia Indonesia terhadap arus kiri yang masih dianggap sebagai ancaman keamanan negara.
Di Yogyakarta, pasca reformasi, penerbit kecil-kecil muncul bak cendawan di musim hujan. Buku-buku tentang ide-ide kiri, yang selama era Soeharto di awasi, tiba-tiba banyak bermunculan dan digemari mahasiswa periode itu, mulai dari buku Marxist klasik hingga pemikir Kiri Baru, Antonio Gramsci.
Situasi sosial-politik Indonesia yang belum menentu membuat pertumbuhan buku-buku kiri sangat subur seakan menjadi referensi atas carut-marutnya keadaan. Namun, tak semua buku kiri bisa beredar bebas, beberapa di antaranya tetap diawasi aparat dan kelompok ormas intoleran.
Pemberangusan buku kiri pernah dialami Muhammad Nursam, pendiri dan direktur Ombak, salah satu penerbit buku sejarah dan biografi di Yogyakarta. Dua di antara banyak buku kiri yang diterbitkan Ombak adalah tentang tokoh gerakan kiri paling berpengaruh di Indonesia, Tan Malaka, yaitu Alimin dan Tan Malaka: Pahlawan yang Dilupakan dan Tan Malaka dan Gerakan Kiri Minangkabau di Indonesia, Malaysia dan Singapura.
Dalam periode 2002-2009, Ombak termasuk subur dalam menghasilkan buku sejarah kiri dan perlawanan. Tahun 2004, penerbit itu pernah ditutup aparat selama seminggu karena menerbitkan buku-buku semacam itu, sebelum akhirnya diperbolehkan aktif kembali.
Nursam selalu mengecam segala bentuk pelarangan buku. Indonesia sudah bergerak melampaui era reformasi sejak 18 tahun lalu, tetapi anehnya hari ini masih takut terhadap buku.
Baginya, buku adalah simbol dari peradaban manusia. Di negara demokrasi, setiap orang berhak untuk mengakses pengetahuan melalui buku apapun.
“Pelarangan buku-buku bukan saja merupakan pemberangusan kebebasan berpendapat, tetapi juga penghilangan sejarah dan pembunuhan peradaban manusia,” ujar Nursam yang juga alumni Ilmu Sejarah UGM. —Rappler.com
BACA JUGA:
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.