SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

YOGYAKARTA, Indonesia — Tes wawancara dalam proses melamar pekerjaan sering menjadi tahap yang paling ditakuti para pencari kerja. Bagi Ida Puji Astuti Maryono Putri, butuh tiga tahun untuk selamat melewati tahap tersebut dan sukses mendapat pekerjaan.
Alumnus Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, dan pemegang gelar master dari Universitas Ateneo de Manila, Filipina, itu tak pernah mendapat jawaban pasti mengapa tak juga sukses menembus aneka tahapan tes ketika mencari kerja hingga tiga tahun lamanya. Perempuan kelahiran Boyolali itu memiliki tinggi tubuh 110 cm, akibat mengalami gangguan kesehatan ketika balita.
Setelah melalui berbagai rintangan dalam hidup, Ida akhirnya merintis Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk mengikis jurang pemisah terhadap difabel di masyarakat.
“Ketika mengurus surat keterangan di Tangerang, seorang polisi berkata, mesin kerja saja ukurannya lebih besar dari badan saya.”
“Apapun kondisi fisik saya, selama saya mampu, tentu tidak akan menjadi masalah. Tapi dunia ini masih sangat idealis, dan konsep itu tidak terjadi pada saya,” kata Ida kepada Rappler, pada pertengahan Juli.
Seorang dokter ortopedi mendeteksi gangguan pengapuran di persendian lengan dan kaki Ida ketika ia berusia 10 tahun. Organ tubuhnya tumbuh dan berkembang, tetapi lengan dan kakinya tidak.
“Sejak usia 3 tahun, orangtua saya tak lelah mencari penawar untuk sakit saya dan fokus pada terapi. Tubuh dan wajah saya berkembang optimal, meninggalkan kaki dan lengan,” akunya.
Ida beruntung, ia dilahirkan dari pasangan orangtua yang sangat menerima dengan kondisinya. Ayahnya bahkan hingga saat ini selalu ingin mengantarkan Ida ke manapun dia beraktivitas. Sekolah tingkat dasarnya dihabiskan di sekolah negeri favorit di Boyolali, sebelum berlanjut kuliah di Jurusan Kimia, Fakultas MIPA Universitas Gadjah Mada dan lulus tahun 2004. Selama masa itu, Ida merasa tak mengalami diskriminasi karena kondisinya.
“Guru di sekolah mengizinkan saya tidak ikut mata pelajaran olahraga, teman-teman sangat membantu. Bahkan penguji saya ketika sidang skripsi membantu menata meja dan kursi agar sesuai dengan postur saya dan presentasi bisa optimal,” ujarnya.
Dunia dirasa berbeda setelah Ida menamatkan kuliahnya. Anak kedua dari tiga bersaudara itu dituntut untuk mandiri dan memiliki pekerjaan dengan bekal ijazah sarjananya. Pencariannya dimulai di Boyolali hingga berburu pekerjaan selama dua bulan di Jakarta namun dengan hasil nihil.
“Setelah wawancara, pasti tidak dipanggil lagi. Saya pernah melamar dua kali di sekolah internasional di Tangerang. Lamaran pertama terhenti setelah tes bahasa Inggris. Lamaran kedua dengan panitia yang sama mengatakan heran, kenapa saya tidak dipanggil lagi setelah tes Bahasa Inggris karena nilai saya lolos di lamaran sebelumnya,” kata Ida mengenang.
“Juga ketika mengurus surat keterangan di Tangerang, seorang polisi berkata, mesin kerja saja ukurannya lebih besar dari badan saya.”
Belajar ke Amerika dan meraih gelar master
Ida lulus kuliah pada 2004. Dengan dukungan tanpa henti dari keluarga, pencarian kerjanya mulai membuahkan hasil.
Ia diterima sebagai pengolah data di Lembaga Kajian Transformasi Sosial (LKTS) di Solo pada 2007 dan bertahan selama lima tahun. Sejak itu, sejumlah pekerjaan lain mulai singgah, di antaranya sebagai kontributor atau penulis lepas. Ida bersama timnya terbiasa bepergian menggunakan transportasi umum mengejar tenggat tulisan.
Upaya berburu beasiswa dan kesempatan belajar di luar negeri juga berbuah manis. Diawali dengan pelatihan pendek di Amerika Serikat pada Juli-Agustus 2010 tentang pemberdayaan perempuan dan difabel, berlanjut menjadi peserta konferensi pariwisata aksesibel untuk difabel pada 2014, pelatihan jurnalistik di Autralia 2015, dan beasiswa untuk master di Global Politics dari Departemen Political Science di Universitas Ateneo di Manila, Filipina.

Ida sukses meraih gelar masternya dan pulang ke Indonesia pada Juli 2017 ini. Bermodal banyak membaca buku, ia tak pernah merasa takut dengan yang asing dan berpetualang di negara lain.
“Yang susah adalah meyakinkan orangtua bahwa saya akan baik-baik saja di luar negeri. Saya sendiri tak takut, karena sejak sekolah sudah sering membaca buku terjemahan dan banyak tahu tentang Amerika dan yang lain,” ucapnya.
Pekerjaan baru sebagai Project Officer di Orgainsasi Harapan Nusantara (Ohana) di Yogyakarta menyambut dan mulai dijalani sejak pertengahan Juli 2017 ini.
Pendidikan untuk semua
Selain bekerja, Ida juga merintis PAUD di Desa Ringinlarik, Kecamatan Muso, Boyolali, sejak 2015. PAUD itu berdiri untuk mengikis jurang segregasi yang tercipta antara masyarakat dan kaum difabel. Ia bercita-cita menciptakan pendidikan yang memberikan sarana terhadap pelajar difabel, sekaligus memiliki sistem yang tidak menganaktirikan difabel, dan mampu membangun jembatan pengertian antara mereka dan masyarakat.
Ia mengatakan, hal ini bermula dari meningkatkan pengertian untuk mengikis diskriminasi dan meningkatkan rasa percaya diri kepada difabel sejak dari lingkungan keluarga.
“Difabel adalah manusia. Satu pengguna kursi roda tak bisa disamakan dengan pengguna kursi roda yang lain. Mereka juga punya potensi dan kebutuhan berbeda.”
“Difabel adalah manusia. Satu pengguna kursi roda tak bisa disamakan dengan pengguna kursi roda yang lain. Mereka juga punya potensi dan kebutuhan berbeda. Keluarga dan lingkungan berperan banyak dalam memberikan rasa percaya diri bagi difabel,” katanya.
PAUD tersebut berjalan dengan bantuan rekan difabel yang lain, Titik Isnaini.
Ida mengaku beruntung tumbuh di lingkungan keluarga yang suportif dan sekolah yang tak membedakan kondisinya. Saat ia masih menjadi seorang pelajar, sekolah hanya melihat Nilai Ebtanas Murni (NEM) sebagai indikator diterima atau tidak, tanpa melihat kondisi fisik.
Namun sistem mengalami perubahan dan kini pendidikan diwajibkan menjadi sekolah inklusi, menyediakan sarana dan fasilitas untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Menurutnya, difabel dan masyarakat butuh ruang yang sama untuk berbaur, agar difabel mendapat kepercayaan diri dan masyarakat juga melihat difabel sebagai anggota komunitas yang sama.
“Seperti perisakan kepada mahasiswa autis di Universitas Gunadarma itu, mungkin lingkungan pendidikan sudah memiliki sarana tetapi sistem pendidikannya belum. Ada jarak antara siswa difabel dan yang lain,” kata Ida.
“Di lapangan, saya dengar dari kawan difabel lain, ada banyak kondisi serupa. Kondisinya tak sesederhana itu. Bagaimana membuat sistem yang bisa menyelesaikan masalah tanpa membuat masalah baru, dengan memanusiakan manusia.” —Rappler.com
Add a comment
How does this make you feel?



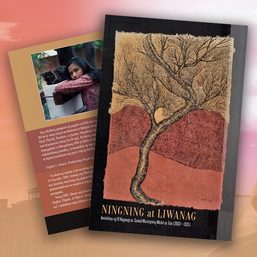
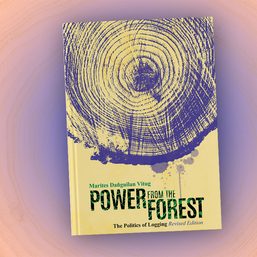
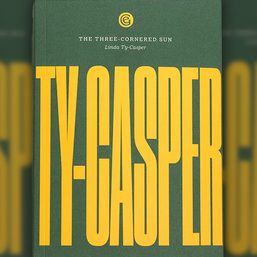

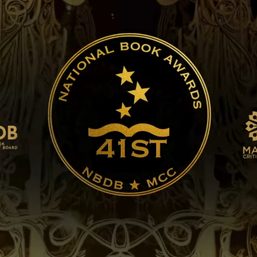
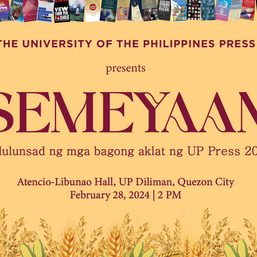
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.