SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.
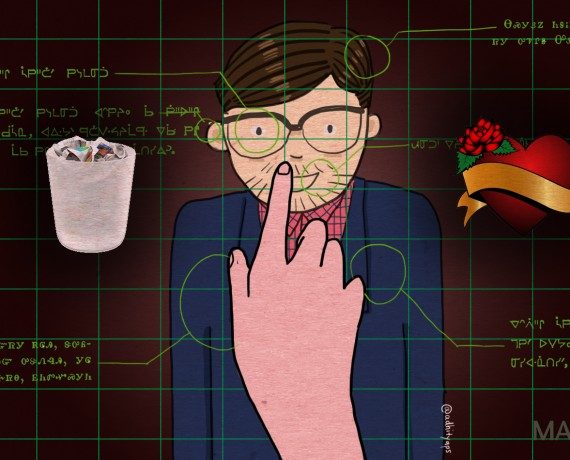
JAKARTA, Indonesia – Berikut adalah percakapan saya dengan seorang lelaki yang baru saya kenal beberapa minggu yang lalu.
Dia: “Aku sukanya film-film yang bikin mikir.”
Saya: *tertarik* “Oh ya? Kayak film apa?”
Dia: “Tahu Inception? Atau yang lebih ringan kayak Jason Bourne.”
Saya: …
Saya: ….
Saya: Ah, I see.
Dan sudah dapat dipastikan tidak akan ada kencan berikutnya lagi dengan lelaki ini. Dan teman-teman saya kembali akan mengatakan hal yang sama ke saya: “Jangan terlalu pemilih gitu, ah!”
Sesekali saya suka memikirkan wejangan ini, bahwa saya seharusnya lebih fleksibel dalam ‘memilih’ laki-laki untuk menjadi pasangan saya. Bahwa hal-hal remeh seperti mengetik ‘wkwkwkwkwkwk’ untuk menunjukkan sedang tertawa atau menggunakan ‘u’ untuk menggantikan ‘kamu’ atau foto profil di WhatsApp-nya adalah foto mobilnya atau saat menonton film di bioskop dia bicara terus sepanjang film, tidak seharusnya menjadi faktor ‘pembatal’ minat saya. Bahwa hal-hal itu tidaklah krusial dan masih bisa ditolerir.
Mungkin karena sifat saya yang berdasarkan tes Myer Briggs adalah INTJ, saya sangat senang menghakimi. Melihat lelaki memakai kalung emas, saya sudah (secara mental dan sering kali diikuti secara harafiah) mundur beberapa langkah.
Kenapa? Sulit dijelaskan, tapi saya merasa bahwa karakter laki-laki yang memakai kalung emas di keseharian itu tidak akan cocok dengan karakter saya.
Sifat pemilih saya semakin menjadi-jadi saat saya mencoba Tinder. Foto profil telanjang dada? Geser ke kiri. Fotonya swafoto semua? Ke kiri. Ada ID Line? Ke kiri. Ada keterangan tinggi badannya berapa? Ke kiri. Sapaan awalnya ‘hey babe’? Ke kiri.
Saya tidak mengatakan hal-hal itu salah. Sama sekali tidak. Untuk beberapa (banyak) orang hal-hal tersebut bahkan tidak masuk radar mereka sebagai masalah. Atau mereka bisa menepisnya begitu saja dan terus melanjutkan hubungan mereka dan mereka menjadi pasangan yang berbahagia untuk selamanya.
Bisa jadi juga sikap saya ini sesederhana karena latar belakang pendidikan saya adalah sastra, sehingga saya terlalu mudah untuk menganalisa ‘teks-teks’ seperti itu.
Saya tidak mencari orang yang sama dengan saya. Saya yang tergila-gila dengan buku ini tidak masalah kalau pasangan saya tidak menikmati baca buku seperti saya asalkan dia masih baca-baca berita atau artikel-artikel informatif di internet.
Saya pecandu kopi namun tidak akan menilai dia yang tidak suka minuman itu sebagai makhluk yang lebih inferior dari saya. Saya yang khatam dengan dunia hiburan Korea Selatan ini juga tidak akan memaksa pasangan saya untuk ikut nonton konser Big Bang bersama saya. Saya paham bahwa kesukaan orang itu berbeda-beda dan memang bukan kesamaan macam itu yang saya cari.
Yang saya cari adalah kesamaan gelombang frekuensi.
Saya selalu percaya manusia di bumi ini dilahirkan dengan frekuensi yang berbeda-beda dan hal-hal kecil macam itu sebenarnya adalah gelombang-gelombang yang menentukan posisi frekuensinya.
Buat saya, hal-hal itu justru yang menentukan apa saya dan dia berada di frekuensi yang sama atau tidak. Apakah kami memiliki konsep yang sama untuk berbahagia.
Saya paham ada hal-hal yang menurut orang lain itu tidak penting dan remeh tapi buat saya hal-hal remeh itu menjadi filter yang penting dalam memilih pasangan untuk membangun hubungan romantis.
Selera musik. Selera film. Selera berpakaian. Cara mengirim pesan. Cara berbicara ke pelayan/supir Uber. Etika di tempat makan. Etika di bioskop. Pemilihan kata lisan/tulisan. Pandangan tentang agama. Pandangan tentang seks.
Pandangan tentang ‘diam di rumah dan tidak melakukan apa pun’. Pandangan tentang mandi cuma sekali di hari libur (pernah ada laki-laki yang berkomentar, “Ih kamu kok belum mandi sih? Nanti aku ilfil lho.” *rolling my eyes*).
Hal-hal seperti itu yang menurut saya menjadi indikasi penting apakah saya kompatibel atau tidak dengan seseorang. Apakah saya bisa bahagia menjalani kehidupan saya dengan dia nantinya.
Jadi saat si lelaki itu mengkategorikan Inception sebagai film yang bikin mikir sementara untuk saya tipe film bikin mikir itu seperti Clockwork Orange atau The Lobster, saya tahu frekuensi saya dan si lelaki ini berbeda. Saya dan si lelaki ini akan memiliki banyak pandangan yang berbeda tentang hidup ini.
Dalam pembelaan saya, saya memang seharusnya menjadi sangat pemilih untuk menentukan pasangan saya. Saya menginginkan pasangan yang sejalan dengan saya, yang bisa menertawakan hal yang sama, yang bisa sama-sama malas keluar rumah dan lebih memilih seharian di kasur tanpa mandi sambil nonton lagi Breaking Bad dan kembali menganalisis semua adegan-adegannya sambil makan cemilan-cemilan tanpa takut mengotori seprai. Saya enggan untuk berkompromi dengan kebahagiaan saya.
Risikonya, ya, memang jadinya saya akan sangat jarang terlibat dalam hubungan. Risikonya, ya, pencarian saya akan lebih lama dari orang-orang lainnya. Dan saya nampaknya mulai bisa berdamai dengan hal ini.
Sekarang hanya tinggal membuat orang-orang di sekitar saya untuk bisa berdamai juga dengan pilihan saya ini. Untuk meyakinkan mereka bahwa saya tidak perlu mengkompromikan kebahagiaan saya hanya karena saya ‘sudah semakin tua’ atau ‘sudah pantas menikah’.
Bahwa menjadi bahagia adalah esensi dari menjalani kehidupan ini dan bagi saya, menjadi ‘terlalu pemilih’ adalah cara saya untuk bisa menemukan kebahagiaan saya bersama pasangan saya nantinya.
Inge Agustin adalah seorang karyawan swasta di sebuah kantor hukum di Jakarta. Dianggap aneh karena mengidolakan Eminem dan Big Bang. Bisa di-mention-mention di @inge_august.-Rappler.com.
Artikel ini sebelumnya terbit di Magdalene
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.