SUMMARY
This is AI generated summarization, which may have errors. For context, always refer to the full article.

Dunia baru saja memperingati Hari Bipolar dan Hari Kesehatan Sedunia. Khusus Hari Kesehatan Sedunia, WHO menetapkan tema Depression: Let’s Talk yang kemudian oleh Kementerian Kesehatan RI diterjemahkan menjadi Depresi: Yuk Curhat.
Banyak pemangku kebijakan, termasuk dokter, begitu sibuk membuka keran dialog dan event untuk meningkatkan kesehatan jiwa masyarakat. Pada saat berbicara kesehatan, tidak bisa dipungkiri bahwa yang menjadi fokus adalah masyarakat sehat, “terkadang” minus tenaga kesehatannya. Sesungguhnya negara akan sehat tanpa mengekslusi siapa pun.
Sebuah fakta yang mencengangkan dibahas dalam Lancet bulan April 2017, bahwa separuh dari dokter di Amerika Serikat mempunyai gejala-gejala burnout (kelelahan emosi terkait kerja, depersonalisasi, dan sebuah perasaan tentang penurunan prestasi).
Sangat mengejutkan bahwa perhatian yang diberikan terhadap permasalahan burnout tersebut sangatlah kecil. Ada keheningan yang justru memekakkan tentang burnout. Padahal dalam hubungan dokter-pasien terdapat hubungan aliansi terapautik sehingga kesehatan jiwa kedua pihak harus dikedepankan dan sama-sama mendapatkan perhatian.
Temuan Lancet menarik untuk sejenak membawa kita memikirkan kondisi para dokter di Indonesia dalam era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Indonesia berhak bangga dengan adanya JKN dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
Bangga karena dunia mengakui keberanian Indonesia memberikan Universal Health Coverage. Empat tahun sudah berselang sejak drama pengesahan Undang-Undang BPJS, kini 175 juta orang telah menjadi peserta JKN dengan hampir separuh pesertanya tidak menggunakan haknya karena termasuk penduduk kelas menengah atas yang lebih memilih membayar sendiri atau membeli asuransi kesehatan tambahan.
Indikator kepuasan rakyat atas kinerja pemerintah dalam bidang kesehatan konon mencapai angka 65 persen. Kabinet Kerja mendapatkan apresiasi, tetapi semoga bukan menari-nari di atas panggung reyot.
Sebagai warga negara, kita harus mau dan jujur otokritik JKN dan BPJS. Jelas implementasi JKN sarat masalah. Tarif JKN ditekan jauh di bawah harga keekonomian, dan dalam tiga tahun BPJS Kesehatan terjadi defisit lebih dari Rp 18 triliun.
Muncul kambing hitam dari mulai rumah sakit yang tidak pro-rakyat, manajemen yang buruk, dokter yang hedon, dan sebagainya. Padahal mereka yang dituduh justru berada dalam posisi pasif sebagai pelaksana dari sistem dan ketidakterbukaan BPJS Kesehatan.
Jika kualitas layanan JKN memuaskan, seperti klaim BPJS Kesehatan tentang tingkat kepuasan peserta lebih dari 75%, lantas apa alasan BPJS Kesehatan membeli asuransi tambahan swasta untuk pegawainya? Kemudian apakah sempat, kita memerhatikan bagaimana dengan kondisi kesehatan jiwa para dokter yang menjadi pemberi jasa layanan kesehatan di era BPJS?
Konsekuensi JKN bagi pelayanan kesehatan jiwa
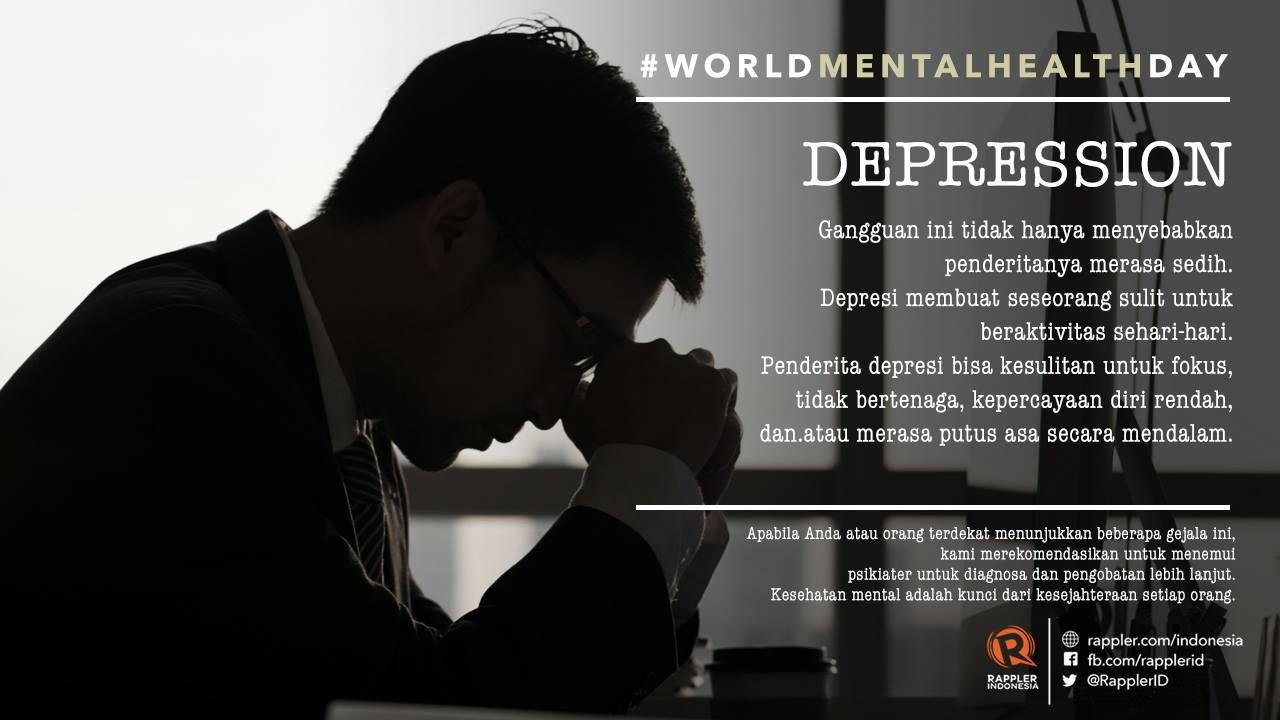
Cobalah untuk para petinggi meluangkan waktu duduk-duduk di bilik poli BPJS pada setting rumah sakit pemerintah. Misalnya, di poli sebuah rumah sakit jiwa pemerintah.
Betul sekali bahwa Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa gratis dari mulai rawat jalan, rawat inap, kualitas obat yang juga bukan sekadar obat generik, ketersediaan obat yang jangka panjang, pelayanan rehabilitasi melalui daycare, pengembalian fungsi sosial dan kerja bahkan tidak sedikit juga terbuka kesempatan mendapatkan lapangan kerja. Dengan kata lain, prinsip-prinsip Undang-Undang Kesehatan Jiwa dan Undang-Undang Disabilitas diindahkan.
Namun dalam perjalanan manajemen ODGJ, ada prinsip-prinsip terapi yang terabaikan. Pada 7 April 2017, Cesar Alfonso, seorang psikiater pakar psikoanalisis dari World Psychiatric Association, mengimbau dalam event Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Cabang DKI Jakarta, agar psikoterapi (berbagai metode intervensi di luar psikofarmaka atau obat untuk menangani masalah kejiwaan) menjadi modalitas terapi depresi karena merupakan hak dari ODGJ untuk mendapatkan penanganan yang tidak invasif.
Alfonso menambahkan, juga terbukti bahwa dengan psikoterapi terdapat efektivitas yang sama dengan pemberian psikofarmaka jika dilihat dari pemeriksaan functional Magneting Resonance Imaging (MRI), sehingga tampak gambaran pertumbuhan otak sampai level molekuler.
Dengan jumlah pasien yang menumpuk, sementara dokter jiwa saat berhadapan dengan setiap pasien disibukkan dengan berbagai kegiatan administratif berupa pengisian rekam medis (yang jika tidak lengkap maka akan dikembalikan oleh bagian rekam medik dan berdampak pada indeks kerja dokter), lembar rujukan BPJS, penulisan resep yang kadang harus dua kali secara terpisah untuk kepentingan administrasi klaim BPJS (7 hari dan 23 hari), lembar kunjungan berikut pasien, lembar pelaporan pasien untuk Indeks Kerja dokter, pengisian billing entry di komputer, dan lain-lain, maka bisa dibayangkan momen pelayanan kesehatan jiwa tersebut begitu singkat sekaligus tak berkualitas.
Akhirnya, modalitas psikoterapi yang disarankan Alfonso tidak bisa diterapkan pada setting rawat jalan BPJS (atau bisa, tetapi dengan mekanisme geser ruangan untuk tidak mengganggu arus pelayanan yang kadang terasa dalam angkutan kota karena pasien berikut sudah melongok di pintu meminta cepat-cepat gilirannya) dan lagi-lagi resep psikofarmaka yang menjadi primadona paradigma penyembuhan utama ODGJ termasuk depresi.
Berbicara psikofarmaka, ada opsi menarik jika melirik negara tetangga terdekat, Singapura. Fee dokter di rumah sakit pemerintah seperti Changi General Hospital yang penulis saksikan sendiri, relatif tinggi sementara harga obat sangat murah.
Ada dua keuntungan dari sistem ini; kekhawatiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahwa dokter menjadi sapi perahan perusahaan farmasi sehingga potensi terjadi kongkalikong gratifikasi pun tercegah dari level preventif, rakyat pun senang saat membayar tagihan obat dengan harga tidak mahal. Dibandingkan dengan harga obat mahal menjadi supremasi perusahaan farmasi maka yang menjadi korban lebih banyak.
Dokter pun akan sulit bekerja dengan jiwa yang sehat jika dalam posisi terdesak oleh banyak pihak. Walaupun hal ini juga diakibatkan oleh proses tender obat era JKN yang ditekan pada harga terendah sehingga banyak spekulan ikut tender karena farmasi besar yang ikut tender e-catalogue tidak memadai jumlahnya.
Kesehatan jiwa dokter
Depresi dan burnout epidemiologinya berbeda, tetapi gejala-gejala burnout lebih lazim di kalangan dokter daripada entitas diagnosis seperti depresi. Harus diwaspadai terdapat tumpang tindih di antara keduanya dengan risiko depresi meningkat seiring dengan tingkat keparahan burnout.
Ada dua dikotomi dalam menghadapi permasalahan burnout itu sendiri, yaitu membingkai burnout sebagai sebuah paradigma kesehatan jiwa, atau sebagai pendekatan sistem. Jika kita fokus pada penyakit individu, maka ada risiko pengabaian dampak praktik-praktik institusi yang justru telah menyebabkan dokter mengalami burnout. Walaupun jarang sekali kita saksikan direktur utama sebuah rumah sakit didemo oleh para dokter di rumah sakit tersebut.
Lantas bagaimana dengan kesehatan jiwa dokter Indonesia? Apakah sehat jiwa atau nrimo? Tidak ada data versi Indonesia, ini masih merujuk pada Amerika Serikat.
Dalam momentum perhatian dunia sedang tercurah pada depresi, wacana harus terbentuk pada level nasional. Baik tentang determinan kesehatan jiwa secara luas, dan secara khusus pada negara-negara berkembang (walau Indonesia ternyata kaya setelah pendataan tax amnesty) yang terbelenggu sistem kesehatan nasional yang sangat membebani, seperti di Indonesia dengan adanya JKN yang masih dalam proses penyempurnaan implementasi.
Memang tidak ada evaluasi tunggal tentang strategi yang paling tepat, Intervensi untuk mengurangi burnout membutuhkan pendekatan campuran intervensi system-focused dan practitioner specific. Tidak bisa dibayangkan sebuah negara yang sedang menerapkan JKN seperti Indonesia kemudian dokter-dokternya mengalami burnout massal sehingga mengganggu well-being dokter, pasien, dan taraf kesehatan nasional. —Rappler.com
Nova Riyanti Yusuf adalah psikiater RSJ Dr. Soeharto Heerdjan dan Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PDSKJI) Cabang DKI Jakarta.
Add a comment
How does this make you feel?
There are no comments yet. Add your comment to start the conversation.